Kuratorial "Vox Populi" (Katalog)
Agus Dermawan T.
Afriani dan “Vox Populi”
Pameran tunggal
Afriani, pelukis otodidak kelahiran Selayo, Sumatera Barat 1974, diberi juluk
“Vox Populi”. Kata ungkapan bahasa Latin itu artinya “suara rakyat jelata”, atau
suara orang kebanyakan. Kata itu dipetik dari ungkapan yang populer ratusan
tahun lalu di belahan dunia Barat, “vox populi vox Dei”, suara rakyat adalah
suara Tuhan.
Judul ini tentu
mengacu kepada karya-karya Afriani yang senantiasa menggambarkan kehidupan
rakyat kecil. Dunia rakyat memang tampil begitu eksplisit, sehingga lukisannya hadir
selayak foto-foto jurnalistik. Namun oleh karena Afriani mengolahnya lewat
proses seleksi obyek dan perenungan atas adegan dan peristiwa, yang nampak di
mata kita adalah sublimasi dari gambaran-gambaran jurnalistik. Dengan begitu
lukisan-lukisannya tidak sekadar menyuguhkan kejadian, tapi juga menawarkan
sejumlah pesan. Dari jajaran kanvas Afriani kita menangkap adanya 2 sifat
presentasi. Yang pertama lukisan yang menggambarkan kejadian dengan sikap yang
netral. Yang kedua lukisan yang mengungkap kejadian dengan upaya menyuratkan
metafora.
Untuk kategori pertama bisa kita lihat lewat “The Forgotten”, “Kuli Malam”, “Calon Bintang”, “Sarimin in Action” dan “MasaNya”. Termasuk “Tak Ada Lagi Tempat Bermain”, lukisan yang dengan detil menggambarkan anak-anak gembira bermain di kawasan berbahaya. Dalam lukisan ini Afriani sanggup menghidupkan atmosfir kehidupan anak-anak tuna hiburan yang sedang asyik bermain di rel sebelah sini, sementara kereta api berjalan mendengus dan mengancam di sebelah sana.
Dalam lukisan-lukisan
kategori ini Afriani nampak tidak ingin berkata-kata jauh selain keinginan
untuk mengungkap rasa empati. Karyanya tidak menyiratkan gugatan atas
kenyataan, misalnya : betapa ternyata semakin banyak generasi baru bangsa
Indonesia yang miskin dan tak berdaya. Afriani memposisikan lukisannya sebagai
potret realitas.
Lukisan-lukisan
kategori kedua terlihat pada “Dilema”, “Menyemir Asa”, “Atas Nama”, “Apa Kabar,Bung!”,
Souvenirs of War” , “Menatap Cahaya Terang" (Pasca Gempa Sumbar) serta “Pewaris
Semangat”. Sebagai pelukis asal Sumatera Barat, bagaimanapun dirinya sering terlibat
dalam alam pikiran yang biasanya terungkap dalam sastra. Pantun yang banyak
kiasan, prosa yang menyampaikan berbagai metafora.
Lukisan “Dilema” menggambarkan para
pedagang kecil berjualan di bantaran kereta api, adalah sebuah rekaman yang
menyiratkan pesan kepada Pemerintah, bahwa rakyat kecil perlu lahan untuk
berusaha. Apabila pihak yang berkewajiban mengelola hajat hidup masyarakat
berdiam saja, maka rakyat kecil seperti pedagang itu selalu dihadapkan kepada
kenyataan gila : berdagang di rel sungguh berbahaya, tapi bila tak berdagang,
mau makan apa?
“Apa Kabar,Bung!” menghadirkan gambar pemulung kardus yang melewati patung Bung Hatta,
Wakil Presiden Republik Indonesia yang mencanangkan pemikiran kesejahteraan
bangsa. Tapi pemikiran itu tak teralisasi jadi kenyataan, sehingga cuma jadi
warisan kata-kata belaka. “Souvenirs of War” adalah gugatan yang atas perang dan
terorisme yang meluluhlantakkan apa saja. Di sini Afriani dengan elok
menggambarkan monumen asap dan debu, lambang kehancuran kehidupan. Lalu dengan
sudut pandang yang indah ia melukiskan situasi pasca gempa di Sumatera Barat
tahun 2009 lalu dalam “Menatap Cahaya Terang" (Gempa Sumatera Barat). Di situ nampak
seorang ibu dan anaknya sedang menatap reruntuhan bangunan di bumi yang koyak.
Ibu dan anak itu optimis untuk terus mengalahkan derita.
"Menyemir Asa”
merekam kontrasitas dua kehidupan. Di belakang seorang bocah yang menyemir
sepatu untuk sesuap nasi, nampak dua anak orang berada sedang memandangi
etalasi toko yang mendisplay barang mewah. Semantara “Pewaris Semangat”
memperlihatkan seorang pengamen cilik yang biasa menyanyikan lagu tentang hidup
yang kalah tetapi tetap semangat dalam menggapai impian, sedang mengagumi patung
Ki Hajar Dewantara, bapak Pendidikan Nasional.
Namun sesakit-sakitnya nasib, perasaan syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan selalu terucap di hati terdalam rakyat jelata. Afriani melukiskan perasaan itu lewat lukisan seorang penjual pisang yang sedang menghitung penghasilannya yang sejengkalan tangan. Atas uangnya yang tipis penjual pisang itu berguman dengan hati tenteram “yah..lumayanlah” , bagai tertulis sebagai judul lukisan.
Merubah paradigma.
Afriani melukis dunia rakyat adalah untuk melaporkan keadaan rakyat kepada masyarakat luas, dan sekaligus untuk menyuarakan hati rakyat kepada siapa pun yang menatap lukisannya. Dengan bahasa realismenya ia ingin lukisannya juga dinikmati oleh rakyat. Namun Afriani menyadari, bahwa upayanya melukis dunia rakyat, dan untuk dinikmati oleh rakyat, hanya merupakan satu noktah belaka dari sejarah panjang seniman yang mencoba merubah paradigma tujuan penciptaan seni. Dari situ kita lantas gampang diingatkan, betapa pada sebentangan masa silam seni lukis (dan seni rupa pada umumnya) sangat acap diciptakan bukan untuk rakyat jelata, atau bukan untuk orang-orang biasa. Dari situ memori kita diajak berjalan menjumpai sederet perupa pengisi sejarah.
Atas Michelangelo yang menggubah mural di
plafon kapel Sistine, Roma misalnya. Pelukis dan pematung ini berkarya untuk
kepentingan Paus dan gereja. Atau Raden Saleh yang melukis potret dan
pemandangan untuk para bangsawan di Jawa, Belanda dan Jerman. Atau pelukis
legendaris Jan Vermeer, Rembrandt sampai Frans Hals yang melayani pesanan
orang-orang kaya di Eropa.
Prinsip penciptaan yang mengiblatkan seni
kepada “yang tertinggi” itu mulai ditolak keharusannya di Eropa pada abad 18.
Dr.Astri Wright, dalam kitab Modern Indonesian Art, Three Generation of
Tradition and Change 1945 – 1990 (Joseph Fischer, ed), pada artikel Painting
the People mencatat, gejala keluarnya para pelukis Eropa dari kecenderungan
di atas diinspirasi oleh Revolusi Prancis. Juga oleh karya-karya Hogarth,
pelukis dan penggambar radikal Inggris. Sejak itu para pelukis dan pematung
mulai mencoba menggambarkan kehidupan rakyat biasa.
Dan umumnya rakyat tersebut
dilukiskan dalam setting yang menghasilkan cerita. Semua ini lantas bisa
dihubungkan dengan Revolusi Industri, di mana rakyat kebanyakan seperti
pengusaha kecil, administratur sampai buruh hadir di masyarakat sebagai
kelompok dominan. Di Indonesia Astri Wright melihat fenomena semacam itu secara
jelas lewat karya Sudjana Kerton, Hendra Gunawan dan Djoko Pekik. Dan
selanjutnya dia harus mencatat nama Afriani.
Masih
dalam halimun sejarah seni rupa Barat, pada masa kemudian pelukis yang biasa
bekerja untuk para bangsawan dan sehari-harinya bermain di istana pemerintahan
mulai berani melukiskan “realitas lain” di balik gemerlap dan tertibnya istana,
seperti yang dicontohkan oleh Francisco de Goya. Keberanian menghadirkan
realitas ini diteruskan pelukis-pelukis zaman setelahnya, seperti Eugene
Delacroix, Ingres, Gericault dan sebagainya. Di sini siapa pun sah untuk
melukis apa saja dan siapa saja di kanvas-kanvasnya.
Di Indonesia seni rupa yang berangkat dari
konsep “melukis rakyat biasa” itu secara proklamatif bergema ketika Persagi
(Persatuan Ahli-ahli Gambar Indonesia) muncul pada 1938. Dalam anjurannya,
Sudjojono, juru bicara perkumpulan itu, mengajak setiap pelukis mencipta dengan
alam pikirannya sendiri sebagai rakyat, dengan dunia hatinya sendiri sebagai
rakyat, dan mengenai lingkungan hidupnya sendiri, lingkungan hidup rakyat.
Sudjojono menganggap bahwa, dengan merengkuh ide yang berangkat dari dunia
sendiri itu akan muncul seni lukis yang jujur, berkepribadian, dan Indonesiawi.
Dan karya-karya rakyat yang kerakyatan ini dianggapnya akan lebih bermanfaat
bagi kebangkitan sebuah negeri, yang dihuni oleh orang-orang biasa. Karena
seniman yang mewakili hati-pikir rakyat adalah spes patriae, penabur
harapan di tanah air. Semangat Sudjojono ini jelas diteruskan oleh Afriani.
Vox populi, vox dei.
Dalam perkembangan pemahaman berkonteks seni lukis, istilah ”rakyat biasa” akhirnya terelaborasi sebagai “obyek-obyek biasa dari orang-orang atau jelata”. Pilihan ini barangkali terkait dengan penafsiran bahwa sesungguhnya, di mana-mana, rakyat adalah (justru) penguasa. Dan rakyat adalah kebenaran yang berkuasa, sehingga muncul ungkapan “vox populi vox Dei”, suara rakyat adalah suara Tuhan. Atau seperti yang dikatakan orator dan negarawan Inggris Edmund Burke (1729-1797), “The People are the masters”, rakyat adalah raja. Lantas pelukis pun, termasuk Afriani, melukis rakyat, memandang dengan serius segala yang ada di tengah rakyat, dan memanifestasikan segala hal yang dilakukan rakyat. Karena rakyat adalah yang utama.
Perluasan pemahaman atas arti rakyat akhirnya
menjadikan seniman seperti Afriani terus melacak posisinya sendiri, yang
sesungguhnya ternyata tidak lebih rendah dari raja, presiden, penguasa,
menteri, hartawan dan sebagainya. Oleh karena itu, pelukis-rakyat yang melukis
tentang rakyat seperti dirinya bukanlah harus mengabdi kepada negara.
Sebaliknya negaralah yang harus mengayomi mahluk yang bernama pelukis, yang tak
lain adalah rakyat. Bicara dalam lingkup politis, bukankah Aristoteles jauh
hari telah menjelaskan, bahwa tujuan dibentuknya sebuah negara misalnya, justru
untuk menyejahterakan rakyat. Dan samasekali bukan untuk yang lain? Pelukis
Afriani sangat mengerti logika ini.
Dari pemahaman ini akhirnya terbaca bahwa
seni yang sifatnya kerakyatan tentulah tidak dimonopoli oleh seni yang dalam
manifestasinya semata-mata menjelas-jelaskan situasi kehidupan rakyat, bagai
yang ditunjukkan oleh “realisme sosial” di Tiongkok era Mao Tse Tung, di Uni
Soviet sebelum reformasi, atau di era Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) tahun
1960-an dulu. Karena dalam setiap lukisan yang dihasilkan oleh elemen rakyat
yang berpikiran sebagai rakyat, senantiasa terkandung nilai-nilai kerakyatan.
Sekalipun yang dilukiskan tidak lagi semata menggambarkan kepengapan hidup
rakyat jelata.
Keapikan lukisan-lukisan Afriani, salah satu
bintang Jakarta Art Awards 2008 (menurut kritikus Bambang Bujono di majalah
TEMPO), menjelaskan dan membenarkan pendapat itu. Rekamannya atas kehidupan
rakyat, dan pilihannya atas sisi-sisi hidup rakyat, tidak diiringi hasrat untuk
berteriak : “Ini lho kondisi rakyat Indonesia”. Ia melukiskan segalanya
lantaran sebuah empati yang dalam, dengan hati dan pikiran yang tenang.
Karena itu, untuk menutup artikel ini
baik apabila ditawarkan sederet pantun klasik yang biasa dibacakan di kampung
halaman Afriani. Sepetik karya sastra lisan dan tulisan yang patut direnungkan
oleh para pengelola negeri :
Bila orang lupakan diri,
banyaklah bala yang menghampiri
Bila orang lupa pakaian
banyaklah kerja yang bersalahan.
Kalau sudah lupakan diri.
alamat bala menimpa negeri
Kalau sudah lupa pakaian,
di sinilah tempat masuknya setan
Lupa diri binasa negeri
lupa pakaian binasa iman.
Agus
Dermawan T.
Kritikus, penulis
buku-buku seni rupa.

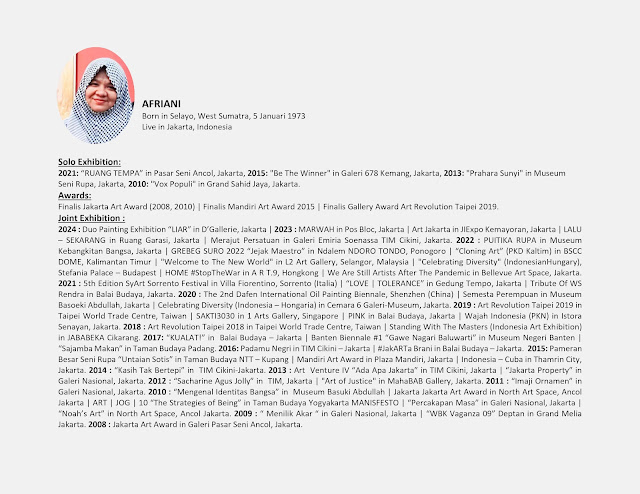

Komentar
Posting Komentar